Analisis Hukum Vonis MK Mencabut Pasal Pencemaran Nama Baik & Hoax

Ilustrasi Revisi UU ITE. (Foto: Istimewa).
Jakarta, law-justice.co - Seperti diketahui, dua orang telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah pasal berkaitan dengan pencemaran nama baik dan berita bohong. Dua orang itu adalah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Untuk permohonan uji materi ini, Haris dan Fatia telah menyerahkan ke kuasa hukumnya yaitu kepada Feri Amsari dkk.
Haris dan Fatia meminta ke MK supaya pasal tentang pencemaran nama baik dan berita bohong dihapus saja. Untuk diketahui, pasal tentang pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
Selain itu, Pasal Pencemaran Nama Baik juga diatur di UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu berbunyi:"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik".
Sedangkan Pasal 45 ayat (3) menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".
Sementara itu untuk pasal berita bohong diatur dalam pasal 14 dan 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14, ayat (1) berbunyi : “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun “.
Adapun ayat (2) berbunyi : “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”’
Sementara itu pasal Pasal 15 berbunyi : “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”
Menurut pemohon, pasal-pasal di atas bisa membungkam kritik dalam negara demokrasi. Pada hal kritik yang disampaikan oleh masyarakat terkait penyelenggaraan negara merupakan salah satu bentuk hak dan tanggung jawab masyarakat yang diimplementasikan melalui partisipasi publik bermakna.
“Oleh karena itu, pendapat dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat kepada penyelenggara negara seharusnya tidak dibatasi secara serampangan. Hal tersebut berdasarkan pada semangat demokrasi pasca-amendemen UUD NRI 1945," beber pemohon.
Putusan MK
Terhadap permohonan uji materi pasal pencemaran nama baik dan berita bohong tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonannya. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK RI, Jakarta, Kamis (21/3/24).
Berkaitan dengan soal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP, MK menyatakan Pasal 310 KUHP Inkonstitusional bersyarat. "Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, `Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah`, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.
`Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah`," tutur Suhartoyo membacakan putusan untuk Pasal 310 ayat 1 KUHP.
Dalam pertimbangannya, MK menilai rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP sebetulnya telah diakomodasi dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ( KUHP baru). Namun, MK menilai ada perbedaan ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP dengan Pasal 433 KUHP baru yakni penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan `Dengan Lisan`.MK menilai unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
"Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 2026, maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan "dengan lisan" yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam persidangan.
"Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap addresat norm atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas," sambung Enny.
Sementara itu, MK memutuskan untuk menolak uji materi tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE karena dinilai telah “kehilangan obyek” setelah pemerintah dan DPR mengesahkan dan mengundangkan perubahan UU ITE yang baru yakni UU 1/2024. Sehingga sebagian materi norma yang diatur dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 telah mengalami perubahan dan sebagian norma dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk perubahan terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon.
Selanjutnya berkaitan dengan uji materi tentang berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, MK menyatakan bahwa Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tak berkekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyebut pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tersebut menjadi `pasal karet` lantaran tidak ada kejelasan terkait ukuran atau parameter.Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai, unsur onar atau keonaran yang termuat dalam Pasal 14 KUHP juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi saat ini.
Sebab masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial.“Dengan kata lain, jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media apapun meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya," jelas Enny Nurbaningsih dikutip dari situs resmi MK.
"Kemudian berita atau pemberitahuan tersebut menimbulkan diskursus di ruang publik, maka seharusnya diskusi tersebut tidaklah serta merta merupakan bentuk keonaran di masyarakat yang langsung dapat diancam dengan hukuman pidana,” lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan Hakim Konstitusi Arsul Sani, MK berpendapat tidak ada kejelasan terkait ukuran atau parameter yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah keonaran tersebut juga dapat diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara.“Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana,” tambah Arsul.
Pada bagian pertimbangan mahkamah yang dibacakan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, MK berpandangan demikian karena menilai, "Rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1945 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.
"Dua rumusan pasal itu dinilai tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara."Dengan demikian, dalil para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum," ujar Enny.
Analisis Hukum
Manusia adalah makhluk sosial yang mutlak membutuhkan komunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja, pendapat satu orang dan orang lain muncul dalam komunikasi, karena kita semua tahu bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu dalam hidup. Kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Demikian pula sebagai bangsa yang berdaulat berdasarkan hukum (rechstaat) bukan kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia mengakui kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berbicara dan kebebasan mengeluarkan pendapatnya
Meskipun kebebasan pendapat secara lisan dan tulisan dijamin oleh UUD namun implementasinya ada rambu rambu yang membatasinya supaya tidak terjadi finah, penghinaan atau penistaan dan sejenisnya yang bisa merusak kehormatan orang lain
Disinilah kita melihat adanya perlindungan terhadap kehormatan secara konseptual, yakni pertentangan antar 2 (dua) hak pribadi, yakni hak berpendapat dengan hak mendapat perlindungan atas kehormatannya.
Pencemaran nama baik dikenal juga dengan pidana terhadap kehormatan. Menurut ilmu hukum pidana, tindak pidana terhadap kehormatan terdiri atas 4 bentuk, yaitu: (1) menista (secara lisan), (2) menista secara tertulis, (3) fitnah, (4) penghinaan ringan. Tetapi dalam KUHPidana (Wetboek van Strafrecht) dimuat juga tindak pidana lainnya yang erat kaitannya dengan kehormatan, yaitu: pemberitahuan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap yang meninggal. Sejauh ini masih belum jelas menurut tindakan mana suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik orang lain, karena banyak faktor yang harus diperiksa.
Oleh karena itu dikabulkannya uji materi terhadap pasal pencemaran nama baik dan berita bohong oleh MK patu disambut dengan gembira. Ini adalah putusan yang baik, karena Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menarik dalam konteks kebebasan berekspresi di Indonesia.
Sejauh ini pasal pasal terkait dengan pencemaran nama baik dan berita bohong telah digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pejabat negara maupun kebijakan pemerintah. Proses kriminalisasi ini tak lepas dari kebijakan hukum pidana khususnya dalam KUHP dan UU ITE yang tidak dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip negara demokratis. Perlu diingat juga bahwa masih ada orang-orang yang dalam proses kriminalisasi karena bersuara kritis demi kepentingan umum.
Bagaimanapun ritik terhadap penyelenggara negara merupakan hak kebebasan berekspresi serta berpendapat."[Kritik] dilindungi dan tidak boleh dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sebagaimana tertuang dalam Prinsip-Prinsip Johannesburg yang juga dikutip dalam pertimbangan Putusan MK
Selanjutnya terkait dengan berita bohong, kita tentunya sepakat dengan pertimbangan hakim MK yang berpendapat bahwa unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal a quo menjadi “pasal karet” yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud "pasal karet" adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolok ukurnya.
Terlebih, dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini yang memudahkan masyarakat mengakses jaringan teknologi informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berkelebihan.
“Sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas yang hal demikian dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut,” ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan pertimbangan putusan.
Bila dicermati memang terdapat ketidakjelasan terkait ukuran atau paramater yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah keonaran tersebut dapat diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara. Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti yakni kegemparan, kerusuhan, dan keributan.
Dari telaahan makna kata “onar atau keonaran” dalam KBBI, makna kata “keonaran” adalah bersifat tidak tunggal. Karena itu, penggunaan kata keonaran dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP berpotensi menimbulkan multitafsir karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.
Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana
Apabila dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945, meskipun sesungguhnya bertujuan memberi masukan atau kritik kepada penguasa sekalipun, hak-hak tersebut akan terancam aktualisasinya. Sebab, yang dapat atau mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan.
Terlebih, tidak adanya ketidakjelasan makna “keonaran” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP tersebut seseorang atau masyarakat yang dianggap menyebarkan berita bohong tidak lagi diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak dapat secara bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin UUD 1945 yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
Berdasaarkan argumentasi yang dikemukakan diatas kiranya sangat tepat pertimbangan hukum hakim MK yang menilai unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 KUHP sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi saat ini. Kini, masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Dalam hal ini dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik.
Hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik yang bukan serta merta dapat dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran dan dapat (dengan mudah) dikenakan tindakan oleh aparat penegak hukum.
Oleh karena itu jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media apapun meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya, kemudian berita atau pemberitahuan tersebut menimbulkan diskursus di ruang publik, maka seharusnya diskusi tersebut tidaklah serta merta merupakan bentuk keonaran di masyarakat yang langsung dapat diancam dengan hukuman pidana
Dengan adanya rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas, sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, tepat sekali apa yang dinyatakan oleh para hakim MK yang menyatakan bahwa dalil para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum
Bagaimanapun putusan MK soal penyebaran berita bohong menjadi angin segar bagi demokrasi di Tanah Air. Sebab, pasal berita bohong kerap digunakan untuk menjerat jurnalis maupun masyarakat sipil oleh sejumlah pihak yang berkuasa. Sejauh ini sudah ada beberapa contoh orang-orang yang tersandung kasus gara-gara pasal itu, seperti Rocky Gerung, Butet Kartaredjasa dan yang lain lainnya.
Namun demikian, meski pasal pencemaran nama baik berita bohong telah dibatalkan MK, masih ada ancaman dari pasal karet dalam kasus berita bohong. Karena masalah penyebaran berita bohong masih ada di UU ITE Perubahan Kedua, yakni dalam Pasal 28 (3) UU 1/2024.
Dengan telah adanya keputusan MK untuk membatalkan pasal tentang pencemaran nama baik dan berita bohong tersebut maka diharapkan Pemerintah dan DPR segera mencabut ketentuan yang sejenis dari UU ITE, KUHP baru, atau aturan pidana lainnya di masa depan.
Bukan hanya DPR dan Pemerintah saja, aparat penegak hukum (APH) pun harus mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini. Pengadilan dan APH harus memperhatikan Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dalam implementasi pasal penghinaan individu dan penyebaran berita bohong.
Penegak hukum tidak bisa menggunakan lagi pasal-pasal tersebut untuk kepentingan penyidikan. Aparat harus menghormati putusan MK yang menjadi dasar hukum baru.Dengan sendirinya penyidikan yang ditangani dengan pasal tersebut harus dihentikan karena hukum yang memayungi sudah tidak ada alias sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh MK.


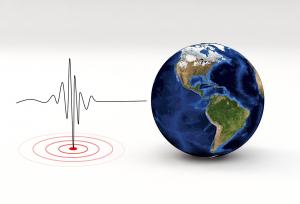

Komentar