Radar Tri Baskoro, Pengamat Sosial Politik
PPKM Awal Kejatuhan Rejim Jokowi & Pandemi dalam Sorotan Teori Chaos
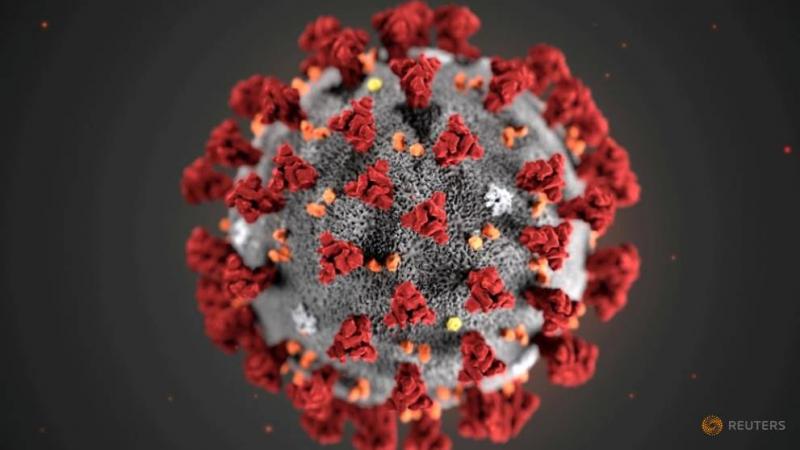
Virus corona (ist)
Jakarta, law-justice.co - Para ahli teori sistem mengatakan bahwa pandemi adalah salah satu contoh dari sistem yang berada dalam situasi chaos. Chaos adalah sistem yang bekerja berdasarkan prinsip "kepakan sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menyebabkan tornado di Texas". Hanya perlu input yang sangat kecil untuk menghasilkan output yang dahsyat luar biasa. Edward Lorentz peletak dasar teori chaos, menyebut fenomena tersebut butterfly effect.
Pandemi Covid-19 ini beroperasi layaknya butterfly effect. Di Cina, sembilan orang makan di bawah semburan AC suatu restoran, kesembilan orang itu positif Covid-19, padahal mungkin cuma satu orang carriernya. Di Washington, seseorang dengan Covid-19 mengikuti latihan paduan suara, dan esoknya separuh anggota paduan suara itu jatuh sakit. DI Korea Selatan seorang lelaki 29 tahun, carrier, mengunjungi sebuah night club dan ia kemudian terkait dengan 54 kasus baru Covid-19.Hanya butuh satu orang pada 20 bulan lalu untuk menginfeksi 200 juta dan membunuh 4,2 juta orang di seluruh dunia sekarang ini. Hal kecil mempengaruhi begitu banyak. Bila AC di restoran dimatikan, mungkin tidak ada yang tertular. Andai jadwal latihan diundurkan, carrier itu mungkin sudah merasa sakit sehingga akan tinggal di rumah atau pergi ke rumah sakit. Pemuda Korea itu sebaiknya memilih menonton TV di rumah ketimbang menari di klub malam. _Butterfly effect!_Secara matematika fenomena chaos mudah ditandai karena perilakunya direpresentasikan oleh pertumbuhan eksponensial, sebuah kurva logistik, seperti huruf J. Andrew dan Strigul (2021) menunjukkan bagaimana sejumlah parameter dalam pandemi Covid-19, seperti total kasus, jumlah kasus harian, jumlah kasus per kapita, dll, membentuk kurva J dari waktu ke waktu.Salah satu implikasi daripada sistem yang chaotic adalah sulitnya meramalkan keadaan. Hubungan sebab-akibat tidak jelas dan tidak linier. Suatu sebab di kesempatan lain bisa menjadi akibat, begitu pula sebaliknya. Di suatu kota boleh jadi Covid-19 nampak sangat ganas, tetapi di kota lain wabah yang sama mudah dikendalikan.Apa yang membedakan keduanya? Sebagian orang berdalih itu lantaran kebijakan, sebagian lagi bilang disebabkan demografi (orangtua lebih mudah tertular), sebagian lain karena cuaca (virus sulit hidup di wilayah tropis), atau ras (orang kulit putih lebih mudah terinfeksi), kesenjangan sosial (orang kaya lebih terlindung). Atau bisa saja pembedanya sekadar keberuntungan. Begitulah chaos, sulit dipastikan, sulit diramalkan.
Chaos adalah bagian yang fundamental dari dunia kita. Bukan kesalahan kita kalau kita tidak tahu kemana chaos pergi. Kita tidak tahu kapan dan dimana wabah itu merebak, dan seberapa parah. Tetapi itu tidak berarti kita tidak punya pengetahuan tentang chaos. Chaos menguasai tetapi tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa.Para ilmuwan mengetahui bahwa virus corona menyebar melalui droplet (sekarang ada bukti bahwa virus itu bisa menginfeksi melalui udara, aerosol). Maka penularan bisa dicegah melalui menjaga jarak (droplet dari nafas dan pembicaraan tidak bisa mencapai jarak lebih dari 1 meter). Ilmuwan juga tahu bahwa virus menyerang saluran pernafasan, karena itu masker bisa melindungi. Virus corona diketahui memiliki masa inkubasi 14 hari, karena itu seorang yang telah diisolasi sepanjang waktu inkubasi tanpa menunjukkan gejala dapat dinyatakan terbebas dari virus.Lebih dari itu semua, para ilmuwan menemukan bahwa virus bisa dibunuh oleh antibodi yang diproduksi oleh tubuh manusia. Asalkan tubuh manusia bisa diajari untuk mengenal keberadaan virus dan memproduksi antibodi untuk membunuhnya, virus bisa dimusnahkan. Pengetahuan itu melahirkan ide tentang vaksin.
Bahwa faktor-faktor fisik tertentu bisa membatasi perilaku virus, menjadikan virus itu tidak sepenuhnya acak atau chaotic. Sistem dengan sifat sedemikian itu disebut deterministic chaos. Dengan memahami sifat-sifat itu maka orang bisa berjaga-jaga dari penularan, mencegah akibat yang parah atau mengobati infeksinya.Artinya, walau dalam situasi chaos orang, kelompok, apalagi pemerintah masih bisa membuat perencanaan. Dalam pandemi, berlaku adagium: semakin cepat, semakin tegas, semakin baik. Dua contoh bisa dikemukakan, yaitu Cina dan Vietnam. Kedua negara tersebut bereaksi sangat cepat, Cina telah mengunci Wuhan pada tanggal 23 Januari 2020, tidak boleh ada warga Wuhan boleh meninggalkan rumah bila tidak ada keperluan sangat mendesak.Sementara Vietnam menerapkan karantina pertama kali di Son Loi tanggal 13 Februari 2020, yang diikuti dengan testing dan contact tracing yang sangat masif. Karantina, diikuti oleh testing dan contact tracing yang masif adalah kebijakan dasar kedua Cina dan VIetnam dalam mengendalikan pandemi. Perlu dicatat karantina berlaku secara universal, kedua negara itu juga menutup bandara. Orang asing sama sekali dilarang masuk sementara warga sendiri diwajibkan karantina 14 hari sebelum boleh keluar bandara.
Tindakan cepat dan tegas kedua negara memperoleh apresiasi dunia karena terbukti berhasil mengendalikan pandemi. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh kasus positif dan jumlah kematian akibat Covid-19. Pada tanggal 1 Agustus 2021 jumlah kasus positif di Cina dan Vietnam tercatat 157.507 dan 93.162, bandingkan dengan Indonesia yang telah mencatat 3,44 juta kasus. Tingkat kematian karena Covid-19 di Cina dan Vietnam (4.636 dan 11.306) sangat rendah dibandingkan Indonesia yang mencapai 95.723 jiwa.Faktor Objektif dan Subjektif Kegagalan Kebijakan Pandemi JokowiKeberhasilan Cina dan Vietnam menanggulangi pandemi terbukti tidak dipengaruhi oleh jumlah populasi dan fasilitas kesehatan. Penduduk Cina hampir 1,5 milyar, sementara Vietnam hampir 100 juta. Fasilitas kesehatan di kedua negara tidak bisa dikatakan mencukupi. Rumah-sakit moderen dan lengkap hanya berada di kota-kota besar, sementara di kota kecil dan pedesaan layanan kesehatan dapat dibilang sederhana. *Kunci keberhasilan mereka terletak pada kesungguhan menjalankan karantina, testing dan contact tracing.*Dan terlebih penting dari segalanya, Cina dan Vietnam sangat fokus dalam menangani masalah kesehatan publik. Kesehatan rakyat menjadi prioritas utama yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan lain, misalnya ekonomi.Adapun kebijakan penanggulangan pandemi di Indonesia telah gagal. *Aroma kegagalan itu sudah terasa ketika pemerintah memilih untuk mengabaikan UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.* Pengabaian ini menyiratkan keengganan pemerintah menjalankan protokol penanggulangan pandemi sesuai dengan standar ilmu kesehatan masyarakat.Sebelum mengupas lebih lanjut perlu ditekankan bahwa suatu kebijakan dikatakan gagal bila subjek kebijakan itu tidak bisa lagi mengendalikan objeknya. Dengan kata lain, kebijakan pandemi gagal bila pemerintah tidak bisa lagi mengendalikan merebaknya virus corona dan mengakibatkan hilangnya kendali atas jatuhnya korban manusia maupun material . Keadaan memburuk dari waktu ke waktu, seperti bola salju yang menggelundung turun semakin besar semakin cepat. Kondisi tersebut dalam teori sistem terjadi bila sistem mengalami siklus umpanbalik positif _(positive feedback cycle)._Kegagalan tersebut bisa dilihat dari faktor subjektif dam tiga faktor objektif yang saling berkaitan, yaitu yaitu faktor teknis penanganan pandemi, ekonomi, dan kepemimpinan pemerintah. Apakah terjadi siklus umpan balik positif di tiga dimensi itu?*Secara subjektif* kegagalan itu dapat dilihat dari dukungan rakyat. Beberapa hari terakhir ini sebagian rakyat mengenakan pita putih atau mengibarkan bendera putih yang melambangkan bahwa mereka telah menyerah, telah berada di ujung kemampuan mengatasi keadaan. Perlambang itu bisa juga dipahami sebagai penantian sia-sia atas kemampuan pemerintah mengatasi pandemi yang telah berlangsung hampir 17 bulan.*Faktor mitigasi pandemi*. Dalam penanganan pandemi saat ini pemerintah justru terdesak untuk mengabulkan tuntutan rakyat yang menghendaki pelonggaran, padahal varian Delta yang jauh lebih cepat menular sedang merajalela. Rakyat dalam hal ini tidak bisa disalahkan sebab mereka sudah 17 bulan hidup tidak menentu, tabungan habis, banyak yang sudah kehilangan mata-pencaharian.Pilihan yg dimiliki pemerintah sangat buruk. Bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi tidak mustahil rakyat akan marah dan hal itu bisa menimbulkan ketak-stabilan politik. Sebaliknya bila pemerintah memenuhi tuntutan tersebut, pandemi akan semakin sulit dikendalikan. Meningkatnya kasus positif di luar Jawa menunjukkan bahwa ancaman itu nyata. Kondisi prasarana-sarana dan alat kesehatan (PSA) kita terbukti sangat terbatas. Kapasitas PSA langsung tumbang ketika kasus harian menyentuh 50.000 per hari. Dengan kata lain, dari sisi teknis penanganan pandemi pemerintah telah terjebak dalam lingkaran umpanbalik positif.Situasi dilematis seperti di atas dalam literatur teori chaos disebut _bifurcation point,_ yaitu suatu titik, in the edge of chaos, dimana tersedia hanya dua kemungkinan, yaitu pilihan kehancuran sistem itu atau munculnya perubahan radikal dimana kualitas-kualitas di dalam sistem berubah secara drastis. Kemungkinan terakhir itu disebut emergence.*Faktor ekonomi.* Sebetulnya bila ekonomi Indonesia dalam keadaan baik jebakan umpan balik positif tidak perlu membawa ke titik bifurkasi. Kalau perbendaharaan negara masih mencukupi kebutuhan karantina sekitar 70 juta penduduk kelas bawah pemerintah masih bisa pegang kendali. Namun ekonomi Indonesia telah berada di ujung tanduk. Dengan kata lain, ekonomi kita juga sedang terjebak di titik bifurkasi.Seperti diketahui, pemerintah membiayai belanjanya dari pajak dan hutang. Pada saat ini hutang pemerintah telah mencapai Rp.6.500 trilyun atau sekitar 40% PDB. Di luar itu, BUMN Indonesia juga berutang hampir Rp.1.000 trilyun.Sementara itu penerimaan pajak justru menurun, pemerintah gagal meraih pajak dari oligarki atau sekelompok orang sangat kaya. Mereka menolak merepatriasi aset-asetnya melalui skema pengampunan (amnesti) pajak. Padahal pembayaran pajak mereka sangat kecil bila dibandingkan dengan proporsi aset yang mereka kuasai. Disinyalir mereka menghindari pajak dengan menyembunyikan asetnya dalam perusahaan yang mereka miliki.
Alhasil pemerintah sangat sulit membiayai operasi rutin pemerintah. Ketika pandemi menerjang dan perekonomian dunia merosot karenanya, ekonomi Indonesia tidak terhindar dari kontraksi. Indonesia pun jatuh ke dalam resesi. Situasi ini mendorong pemerintah menjalankan kebijakan counter-cyclical, yaitu mendorong permintaan total dengan cara menurunkan pajak dan meningkatkan belanja pemerintah. Kebutuhan pembiayaan meningkat sementara pandemi juga menambah pengeluaran untuk macam-macam bansos, vaksin, insentif nakes, PSA dan pemulihan ekonomi. Pertanyaannya, darimana uangnya?Maka di bidang ekonomi pun pemerintah terjebak dalam positive feedback loop. Apapun yang pemerintah lakukan malah memperburuk keadaan. Hutang pemerintah sudah terlalu besar untuk ditambahi hutang baru menutupi beban pandemi dan kebijakan countercyclical. Menambah hutang (termasuk mencetak uang) menjadikan keuangan negara semakin rentan, sementara kalau tidak berhutang pandemi akan menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada kemampuan pemerintah.*Faktor kepemimpinan nasional.* Ketika negara berada dalam masalah nasional yang besar dan ekonomi yang berat, negara masih selamat bila ada kepemimpinan nasional yang terpercaya. Celakanya kepemimpinan nasional berada dalam lingkaran umpanbalik positif yang sama.Kepercayaan rakyat bukan aset bagi kekuasaan Jokowi. Selama tujuh tahun berkuasa, rakyat mempersoalkan ucapan dan janji Presiden Jokowi yang bukan saja tidak ia tepati bahkan dilanggarnya sendiri. Belum beberapa lama lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa UI menggelari Jokowi sebagai King of Lip Services.Bukan cuma Jokowi, mahasiswa menjuluki Wapres Maruf Amin sebagai King of Silent, sementara Ketua DPR Puan Maharani dijuluki Queen of Ghosting. Ketidakpercayaan itu meluas ke kalangan intelektual terkait statistik pandemi. Hampir tidak ada orang yang mempercayai statistik Covid-19 yang disampaikan pemerintah. Statistik itu undercounting, sebagaimana dapat disimpulkan dari laporan situs Our World in Data.
Merosotnya kepercayaan rakyat adalah harga yang harus dibayar Jokowi atas semua tindakan dan kebijakannya selama ini. Secara umum ada empat hal yang telah meruntuhkan citra demokratis, populis dan reformis yang dibangun oleh Jokowi sejak pilgun DKI 2012. Pertama, Jokowi telah dianggap sebagai pemimpin otoriter. Ia tidak sungkan menangkap dan memenjarakan orang-orang yang beroposisi kepada dirinya. Puluhan orang telah dipenjara dengan berbagai tuduhan, mulai dari penghinaan, hoax, fitnah dlsb. Hampir semua yang dipenjara berasal dari kubu oposisi. Kebanyakan pendukung Jokowi bebas, walau melakukan pidana yang sama.*Faktor kedua* adalah kebijakan Jokowi mengamputasi KPK. Sekarang KPK dipimpin oleh orang yang dulu pernah dipecat oleh KPK. Orang itu berasal dari institusi kepolisian yang beberapa tahun sebelumnya beberapa jenderalnya bertarung sengit melawan KPK setelah menjadi tersangka dan seorang diantaranya gagal menjadi Kapolri. Masyarakat memandang langkah Jokowi ini sebagai upaya memandulkan KPK sebagai lembaga anti-rasuah.*Faktor ketiga* adalah kebijakan Jokowi yang mengesahkan UU Cipta Kerja. Undang-undang itu telah menimbulkan kemarahan buruh, petani, aktivis HAM dan lingkungan hidup, masyarakat adat, dsb.Last but not least, selama hampir 7 tahun berkuasa Jokowi telah mengembangkan narasi pecah-belah bangsa. Narasi itu semula dimaksudkan untuk mengikis terorisme tetapi kemudian berkembang menjadi narasi anti muslim pribumi, atau sering disebut kadrun. Kadrun adalah kependekan dari kadal gurun. Kata itu mengacu kepada kelompok masyarakat Arab yang kita ketahui mendiami wilayah padang pasir di Timur Tengah.Istilah itu dipergunakan untuk mengejek kelompok masyarakat Arab Indonesia yang dianggap menjadi cikal bakal terorisme di Indonesia. Istilah itu dengan sendirinya bersifat rasis. Namun Sekarang bukan cuma etnis Arab tetapi siapapun yang mengritik Jokowi, apakah ia terhubung dengan terorisme atau tidak, adalah kadrun.
Keempat faktor di atas menyulitkan Jokowi untuk menjadi pemimpin pemersatu dan inspiratif. Dengan sendirinya upaya Jokowi belakangan ini yang meminta rakyat bersatu-padu menanggulangi pandemi, diabaikan publik. Komen medsos mentertawakan himbauan itu, mereka bilang "Kalau susah minta bersatu, jabatan komisaris dibagi-bagi ke teman sendiri."Sudah sejak nenek moyang kita dulu, kita melihag kepercayaan sebagai fenomena dengan umpanbalik positif. "Sekali lancung ke ujian," kata orang tua kita, "…seumur hidup orang tak percaya." Cukup sekali anda melakukan kecurangan, selanjutnya seluruh dunia seumur hidup orang tidak akan mempercayai anda.Lantas apa pengaruh kegagalan kebijakan pandemi terhadap politik Indonesia. Ini subjek tulisan berikutnya
Komentar