Desmond J Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Badge Award, Penanda Era Panoptikon Telah Tiba?

Desmond J Mahesa
law-justice.co - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bakal memberikan hadiah berupa badge atau lencana kepada masyarakat yang aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di sosial media. Pengumuman itu, disebarkan secara langsung melalui akun Instagram resmi @ccicpolri pada Kamis (11/3) lalu sebagaimana banyak diberitakan media.
Segera program pemberian lencana penghargaan ( badge awards) ini mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat sehingga menuai pro dan kontra. Para pengamat dan pegiat sosial pada umumnya menolak progam ini karena dampak negatif yang bisa ditimbulkannya.
Korban yang sudah jatuh sebagai konsekuensi patrol polisi virtual sudah ada. Apalagi nanti akan ada pemberian lencana penghargaan kepada masyarakat yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana lewat sosial media.
Pada akhirnya munculnya gagasan untuk memberikan lencana penghargaan kepada masyarakat itu juga disebut sebut menandai lahirnya era panoptikon yang berdampak luas pada jaminan kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia. Apakah memang demikian kenyataannya ?
Menuai Pro-Kontra
Pemberian penghargaan khusus bagi pelapor adanya kejahatan sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerapkannya bagi anggota masyarakat yang berani memberikan laporan adanya tindak pidana korupsi kepada KPK. Penghargaan diberikan berupa insentif dan diberikan tidak secara terbuka. Tentu hal ini dimaksudkan untuk kepentingan perlindungan kepada para pelapornya
Selain itu, secara normative pelapor mendapatkan jaminan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, maupun perdata atas laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya. Kecuali laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik atau maksud maksud tertentu yang menyalahi ketentuan yang ada. Jika terjadi ancaman, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan keamanan kepada mereka.
Meskipun soal lencana penghargaan itu sebenarnya bukan hal yang baru namun kehadirannya tetap menuai kontroversi dimasyarakat kita.Dan seperti biasa, lahirnya sebuah kebijakan memang selalu memunculkan pro dan kontra.
Evita Nursanty anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP mendukung langkah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang akan memberi Badge Award (penghargaan) kepada orang yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di internet atau sosial media.
Menurutnyapemberian penghargaan itu dalam rangka mengungkap kasus terselubung dan sulit diungkap, seperti kasus kasus penipuan, pencurian identitas atau data, carding, cyber espionage, antara lain melalui serangan malware, phishing, hacking dan lainnya.
“Cukup banyak jenis tindak kejahatan yang ada di internet yang belum disadari publik. Karena itu, kita mendukung langkah Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, karena ini akan mendorong publik lebih aware mengenai kejahatan di internet, dan mendorong partisipasi mereka untuk makin aktif melaporkan kejahatan siber,” ujar Evita seperti dikutip gesuri,id. 21/03/21.
Masih menurut Evita, selama ini perhatian publik terkait isu UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya berkutat pada urusan pencemaran nama baik saja. Padahal, ada banyak jenis kejahatan yang terjadi yang sangat merugikan masyarakat, pemerintahh dan dunia usaha. “Belum lagi dengan kasus kesusilaan, perjudian, pemerasan dan atau pengancaman, berita bohong dan lainnya. Jadi isu ITE itu bukan melulu soal pencemaran nama baik,” katanya.
Dukungan pemberian lencana juga datang dari Kompolnas meskipun ada persyaratan yang mesti dipatuhinya. “Agar pemberian penghargaan ini efektif, maka harus dilihat dan ditinjau terlebih dulu hasilnya. Dibutuhkan waktu untuk melihat hasil laporan dan menganalissisnya” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti sebagaimana dikutip MNC Portal Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/3/2021).
Oleh karena itu menurutnya, Polri harus mempunyai indikator jelas siapa yang bisa diberi penghargaan Badge award sehingga tidak sembarang memberikannya.
Meskipun ada dukungan dari DPR dan Kompolnas, namun rencana pemberian lencana kepada masyarakat itu banyak juga mendapatkan penolakan karena khawatir dampak yang ditimbulkannya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti misalnya, menyebut ‘Badge Awards’ secara tidak langsung seperti membangkitkan kembali Pamswakarsa.
Pamswakarsa atau pasukan pengamanan masyarakat swakarsa adalah kelompok masyarakat yang dibentuk TNI di akhir masa Orde Baru untuk menghalau para mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR 1998. “Ini bagaikan Pamswakarsa versi digital. Polisi membentuk kelompok tertentu di golongan masyarakat yang dapat mencabut kebebasan masyarakat lain,” tutur Fatia seperti dikutip oleh media Selasa.
Senada dengan Kontras, Asfinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan dampak dari iming-iming pemberian lencana akan menyuburkan praktik adu domba. Adu domba karena penggunaan UU ITE yang multitafsir melalui pasal pasal karetnya. Menguatnya penggunaan UU ITE tidak lain bakal melahirkan korban-korban baru. “Bukan tak mungkin sewaktu-waktu kita sendiri yang kena,” kata Asfinawati, Selasa (16/3/2021).
Kekhawatiran akan munculnya dampak negatif di masyarakat juga di sampaikan oleh Treviliana Eka Putri seorang peneltii dari Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, pemberian penghargaan lencana atau badge award oleh polisi virtual untuk warganet yang melaporkan konten negatif dinilai dapat memicu konflik horizontal ditenga h masyarakat Indonesia.“Pemberian badge award ini supaya warganet aktif melaporkan, tapi semestinya ada konfirmasi dulu dan edukasi, bukan semangatnya saling melaporkan. Mekanismenya juga mesti ditinjau kembali, basisnya apa. Kalau ada keresahan, keresahan seperti apa,” tuturnya seperti dikutip Gatra.com 20/03/21.
Sementara itu Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Iqrak Sulhin juga mengingatkan pemberian Badge Awards berpotensi memicu perpecahan masyarakat Indonesia.“Secara hipotetik bisa menciptakan ketegangan baru di masyarakat,” ungkap Sulhin seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (17/3/2021). Pasalnya mana unggahan yang pantas dilaporkan atau tidak itu belum ada kriterianya. Selain itu, menurut dia upaya tersebut juga akan memicu perilaku kolektif publik yang tidak terukur sehingga ini berbahaya
Mengingat pada saat yang bersamaan, pengakuan dalam bentuk-bentuk simbol seperti pemberian lencana tersebut masih laku di Indonesia.“Sehingga akan mungkin banyak laporan-laporan yang sebenarnya bukan masalah yang sesungguhnya. Terlebih dalam konteks demokrasi dan kebebasan berekspresi,” tuturnya.
Belum lagi, kemungkinan pelaporan karena unsur ketidaksukaan belaka. Misalnya, dia menuturkan, Badge Awards dapat membuat seseorang semakin terdorong dan berani melaporkan unggahan yang dianggap berseberangan dengan pemahaman politik orang yang melaporkannya.
Mulai Makan Korban
Pemberian lencana penghargaan kepada masyakat yang aktif melaporkan adanya tindak pidana di sosial media memang baru sebatas rencana. Namun kehadiran kebijakan itu nantinya akan melengkapi kebijakan yang sudah ada yaitu polisi virtual atau virtual police yang sekarang kabarnya sudah aktif melakukan ronda.
Hasil tangkapan ronda yang dilakukan oleh polisi di sosial media antara lain berhasil menangkap seseorang karena unggahannya di sosial media.Hasil tangkapan yang telah membuat heboh karena dinilai mengandung kontroversi di dalamnya.
Menurut laporan media, pada hari Senin, 15 Maret 2021 yang lalu, seorang warga Slawi, Jawa Tengah dengan inisial AM ditangkap oleh anggota Polresta Surakarta karena menulis komentar di Instagram yang dianggap menghina Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan berawal ketika pada hari Sabtu, 13 Maret, AM menulis komentar di sebuah post Instagram tentang Gibran yang meminta semifinal dan final Piala Menpora digelar di Surakarta.“Tau apa dia tentang sepak bola, taunya dikasih jabatan saja,” tulis AM via insagramnya. Meskipun AM akhirnya dilepaskan setelah merekam permintaan maaf yang kemudian diunggah ke akun Instagram Polresta Surakarta, namun kejadian itu tak urung membuat masyarakat lain menjadi trauma.
Bagaimana tidak trauma karena penangkapan itu memunculkan kejanggalan kejanggalan yang mengindikasikan adanya faktor kekuasaan yang bermain didalamnya. Sebagai contoh meskipun AM terdaftar sebagai warga Tegal, namun justru dia disanksi oleh Polresta Surakarta, yang `kebetulan` merupakan domisili serta wilayah kepemerintahan Mas Wali Kota Surakarta.
AM yang warga Slawi itupun di soal hanya karena dalam kolom komentarnya ia menulis "Tau apa dia tentang sepak bola, taunya dikasih jabatan saja," yang dinilai mengandung unsur hoaks alias berita dusta.
Kata "dikasih jabatan" itulah rupanya yang menjadi akar permasalahan yang menurut tafsir aparat yang menangkapnya dinilai sebagai hoaks atau berita dusta.Karena menurut polisi, Gibran menjadi Wali Kota oleh karena menang Pemilu, bukan lantaran hasil pemberian dari bapaknya yang menjadi Presiden Indonesia. Padahal, frasa dikasih jabatan juga bisa berarti jabatan itu ialah pemberian dari Tuhan atau karena nasib baiknya.
Dalam kaitan ini Polisi mengklaim bahwa keputusan untuk menjerat AM didasarkan pada ilmu pengetahuan nan empiris dan data yang ada. Mereka juga mengklaim sudah konsultasi dengan ahli bahasa, pidana, serta ahli ITE sebelum memanggil pelakunya.Namun, sayangnya, kita tidak tahu ahli siapa saja yang dilibatkan pada kasus itu mengingat tidak ada transparansi dalam proses penegakan hukumnya.
Dari kasus tersebut kita bisa memetik pelajaran berharga bahwa ternyata begitu lebarnya bias sebuah kata yang mampu mengirim seseorang ke dalam penjara. Sebuah kata bisa ditafsirkan maknanya secara beragam dan sayangnya tafsir itu bisa dimonopoli oleh aparat penegak hukum yang menanganinya. Jika tafsir itu menggunakan pasal pasal UU ITE yang menyimpan pasal pasal karet didalamnya maka semakin mudahlah untuk menjerat seseorang ke dalam penjara.
Lagi pula kalau mau konsisten mengikuti pernyataan dari Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa laporan-laporan dengan pasal UU ITE yang bersifat delik aduan dilaporkan langsung oleh korbannya. Apakah dalam kasus AM diatas yang menjadi korban dalam hal ini Gibran Rakabuming telah melaporkan sendiri kasusnya ? Jika Gibran sendiri tidak lapor, lalu atas dasar apa aparat kemudian memproses kasusnya ?
Berdasarkan studi kasus ini membuktikan bahwa keberadaan Virtual Police justru dapat mengancam demokrasi dan menciptakan ketakutan baru di tengah masyarakat ketika ingin melontarkan kritik kepada pemerintah yang berkuasa.Apalagi kalau nanti di tambah dengan adanya pemberian lencana penghargaan kepada para pelapornya. Maka peluang ini bisa dimanfaatkan untuk melaporkan orang orang yang tidak disukainya kepada polisi virtual berbekal sebuah unggahan di sosial media yang sebenarnya biasa biasa saja.
Menuju Era Panoptikon ?
Kasus warga Slawi Tegal yang dicokok aparat karena unggahan di insagramnya yang mengkritik Walikota Surakarta bisa jadi merupakan puncak gunung es permasalahan pengggunaan hak mengemukakan pendapat di Indonesia.
Salah satu permasalahannya diduga karena di dalam UU ITE ada pasal karet yang bisa digunakan sesuai dengan selera penafsirnya. Sadar akan hal ini beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi pernah mengusulkan agar UU ITE di revisi saja. Namun gagasan itu ternyata berhenti hanya sebatas gagasan belaka. Faktanya UU ITE tidak di usulkan oleh pemerintah sebagai UU Prioritas untuk dibahas di Prolegnas 2021 pada hal itulah satu satunya cara untuk merevisinya.
Sementara UU ITE batal di revisi, pihak kepolisian Republik Indonesia sudah bertindak lebih maju dengan membentuk polisi virtual atau virtual police yang saat sudah melakukan ronda di sosial media. Bahkan untuk melengkapi pembentukan polisi virtual telah di usulkan adanya pemberian lencana penghargaan bagi warga masyarakat yang menemukan tindak pidana di sosial media.
Maka patut diduga berdasarkan adanya rangkaian fakta diatas, Indonesia saat ini memang sedang memasuki era baru yaitu era Panoptikon yang dulu juga pernah terjadi pada masa orde baru (orba ) berkuasa.
Panopticon atau panoptisisme ialah mekanisme atau strategi bagi beroperasinya kekuasaan negara. Ditinjau dari sisi historisnya, teori panoptisisme itu dicetuskan filsuf pascamodernisme Michel Foucault. Foucault mengambil ide panoptisisme dari model arsitektur rancangan fi lsuf Inggris Jeremy Bentham yang disebut panopticon.
Panopticon berupa bangunan melingkar di bagian luar dengan menara di tengah-tengahnya. Menara itu dilengkapi jendela besar yang terbuka untuk melihat ke sisi dalam bangunan melingkar disekitarnya. Bangunan melingkar di sisi luar dibagi menjadi sel-sel penjara. Setiap sel punya dua jendela, satu di dalam menghadap jendela menara dan satu jendela lagi di bagian luar sehingga memungkinkan cahaya menembus dari sel yang satu ke sel lainnya.
Sel-sel itu terlihat seperti sangkar yang sangat banyak jumlahnya. Sel-sel itu bisa digunakan untuk menempatkan orang gila, pasien, orang yang dikutuk, tahanan, buruh, atau anak sekolah juga bisa. Sementara pengawas akan ditempatkan di menara yang berada ditengah tengahnya. Karena efek cahaya dari balik sel, pengawas bisa mengamati orang-orang yang berada di dalam sel-sel penjara yang mengelilinginya.
Dengan adanya bangunan model panopticon maka efeknya adalah bisa menciptakan dalam diri para penghuni sel kesadaran bahwa mereka merasa diamati terusmenerus oleh orang yang bertugas mengawasinya. Sehingga secara otomatis akan menghadirkan fungsi kekuasaan hadir disana.
Alhasil melalui panopticon ini segala sesuatu dikesankan agar penghuni penjara merasa berada dalam pengawasan permanen meski pengawasan itu sebenarnya tidak selalu ada. Karena merasa diawasi terus-menerus, maka mereka yang berada di dalam sel penjara akan patuh dan disiplin mematahi ketentuan yang ada di penjara sesuai keinginan pihak yang mengawasinya.
Di era modern saat ini, sesungguhnya fungsi bangunan Panoptikon ini sudah digantikan oleh teknologi yang lebih canggih kamera CCTV misalnya. Dengan adanya kamera CCTV tersebut maka kita merasa harus patuh (misalnya tidak mencuri) karena ada kamera yang mengawasinya. Orang bertuhan juga merasa gerak-geriknya diawasi selama hayat di kandung badan oleh Tuhan yang tak terlihat secara kasatmata.
Pada zaman Orba dulu, fungsi Panopticon ini dimainkan oleh aparat negara khususnya melalui polisi, tentara bahkan Babinsa. Gerak gerik rakyat diawasi sedemikian rupa jika ada indikasi melawan kekuasaan negara maka langsung di “amankan” agar tidak merepotkan penguasa.
Kini ditengah pandemi virus corona ada aroma memanfaatkan pengawasan ala Panopticon untuk mempertahankan kursi penguasa.Inilah yang menjadi kekhawatiran Agamben di Italia, yakni menjadi alasan bagi tindakan dan kebijakan represif terhadap rakyatnya.
Sebagai contoh dalam salah satu surat telegram dari Kapolri tertanggal 4 April 2020 yang lalu telah dinyatakan bahwa penghinaan terhadap presiden dan pejabat dapat dikenakan pasal pidana.Bahkan, salah satu surat menginstruksikan agar patroli siber dilakukan di dunia maya guna memantau perkembangan opini selama pandemi virus corona. Bukan tidak mungkin ini menjadi kebijakan Panopticon penguasa yakni dengan mengawasi individu-individu melalui infrastruktur sosial media.
Perasaan akan diawasi ala panoptikon ini juga terlihat dari bagaimana seorang jurnalis diancam dibunuh setelah menulis beberapa berita mengenai rencana kebijakan Presiden setelah mengunjungi sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat ketika era normal baru akan dibuka. Kasus tersebut menandai bahwa gerak-gerak masyarakat semakin diawasi tanpa sepengetahuan yang diawasi kala pandemi ini – entah oleh siapa.
Saat ini ditengah pandemi virus corona, bangsa Indonesia merasa diawasi kebebasan berpendapatnya melalui seperangkat alat alat negara seperti UU ITE (yang mengandung pasal karet), polisi virtual sampai dengan pemberian lencana penghargaan kepada warga negara yang berjasa. Adanya seperangkat “alat pengawas” yang berfungsi sebagai bangunan panopticon tersebut akhirnya membuat warga negara berpilkir berulangkali untuk menggunakan hak hak menyatakan pendapatnya.
Kondisinya bertambah parah manakala aparat negara yang menangani penegakan hukum yang berfungsi sebagai Panopticon itu tidak bekerja secara adil untuk semua warga. Sehingga hal ini semakin membuat rakyat kebanyak menjadi ciut nyalinya. Bukti bukti sudah banyak terhidang di sosial media mulai kasus Abu Janda dkk yang kebal hukum sampai kasus madam Bansos dan anak pak Lurah yang diduga ikut menikmati dana Bansos corona.
Sementara itu kalau kasus kasus menyangkut orang orang yang bersebarangan pendapat dengan penguasa maka aparat negara terkesan begitu sigap untuk menangkap dan memprosesnya. Aroma tebang pilih begitu terasa sehingga membuat kecut warga yang ingin menggunakan hak haknya.
Datangnya era Panopticon inilah yang membuat rakyat merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena keadilan sulit didapatnya. Yang untung adalah penguasa karena bisa menggunakan sarana kekuasaan yang dimilikinya untuk menjalankan agenda agenda menyelewengnya tanpa ada pihak lain yang berani mengontrolnya.
Memang ditengah pandemi virus corona ini di banyak negara malah meningkatkan pengawasan (surveillance) ala panopticon terhadap warga negaranya. Kondisi ini akhirnya mengarah pada apa yang disinyalir oleh Foucault, bahwa masyarakat akhirnya hanya menjadi objek atas penaklukan (subjugation) dan kontrol di bawah praktik negara. Apakah Anda juga merasa kondisi ini sedang terjadi di negara kita ?

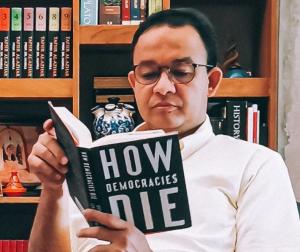


Komentar